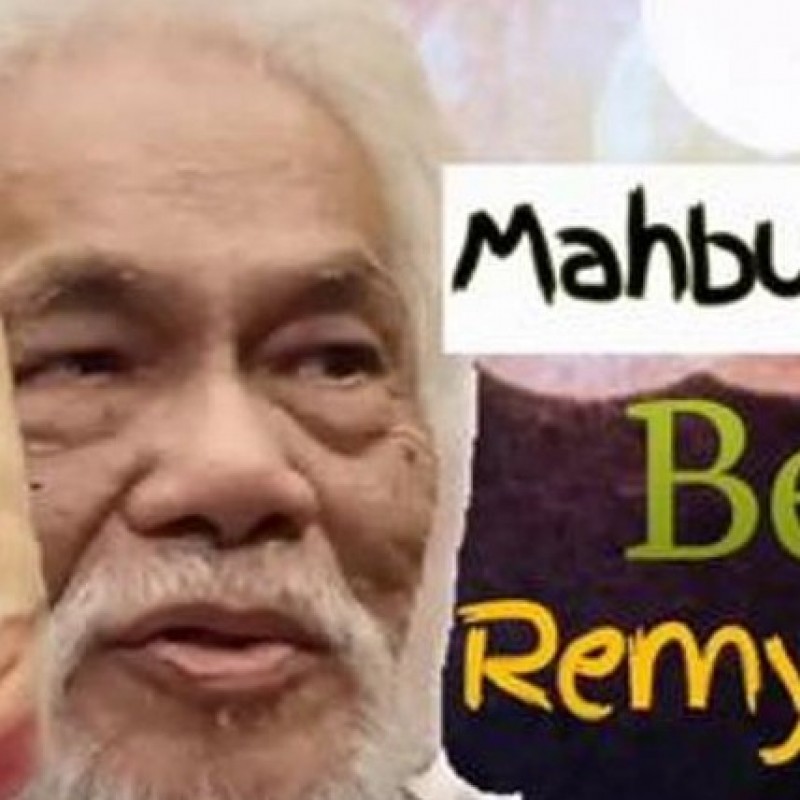Catatan Setahun NU Online Jabar (3): Hubungan Organisasi dengan Media
Selasa, 3 Agustus 2021 | 07:40 WIB
Oleh Iip D. Yahya
Tak terasa, NU Online Jabar berusia satu tahun. Kawan-kawan di Media Center PWNU Jabar, menyingkatnya NUJO. Saat menerima amanah merintis subdomain ini, saya tak berpikir panjang, bismillah saja. Perjalanan satu tahun ini cukup dinamis. Pemberitaan kegiatan NU di Jawa Barat terangkat signifikan. Pemikiran sejumlah ajengan juga tersampaikan kepada publik yang lebih luas. Untuk tingkat ormas Islam, website kami cukup diperhitungkan.
Sebagai penyuka sejarah, saya coba menulis refleksi dan membangun impian atas hubungan organisasi dengan media. Di wilayah Jawa Barat, NU Cabang Tasikmalaya pernah memiliki majalah yang bernama Al-Mawaizh. Dokumen majalah ini masih lengkap dan isinya bisa dipelajari secara saksama. Dari pembacaan atas majalah itulah tulisan ini bersumber.
Saya selalu teringat ucapan Kiai Muchit Muzadi pada awal tahun 2000-an. Bersama kawan-kawan Syarikat, kami beberapa kali berdialog dengan beliau. “Dulu, jadi anggota NU itu sulit.” Mendapatkan pengakuan sebagai anggota (member) harus melalui berbagai ujian. Anggota bukan sekadar jamaah (follower).
Pernyataan Mbah Muchit itu diperkuat dengan data dalam Madjallah Al-Mawaizh terbitan NU Cabang Tasikmalaya (1933-36) yang mengabarkan ihwal “restrukturisasi” keanggotaan NU berdasarkan ketaatan membayar iuran bulanan. Pengurus membagi dua kategori anggota: setuju dan setia. Anggota yang setia, selain sepakat dengan prinsip-prinsip jamiyyah NU juga selalu memenuhi kewajiban iuran bulanan, merekalah yang tetap diakui sebagai anggota dan yang hanya setuju dilepas keanggotaannya.
Anggota NU sangat terpilih, sementara jamaah NU tak terhitung pasti banyaknya karena setiap anggota hampir dipastikan memiliki sejumlah jamaah. Dengan cara ini, tidak heran jika anggota NU benar-benar terseleksi, berkualitas, dan militan. Organisasi NU menjadi lincah karena strukturnya yang ramping. Bukankah ini prinsip manajemen yang modern dan mutakhir? Sentuhan “tangan dingin” Ketua Tanfidziyah HBNO Mahfoezh Siddik, terasa efeknya di tingkat cabang.
Hubungan organisasi antara cabang dan hoofdbestuur pun terasa sangat akrab. Dalam sebuah surat-menyurat antara Ketua Tanfidziyyah Soetisna Sendjaja dan Rais Aam Syuriyah HBNO Hadlratussyekh Hasjim Asj’ari, terbaca sapaan ayahanda dan ananda. Dalam keterbatasan teknologi komunikasi dan transportasi saat itu, keakraban dalam surat menyurat membuat HBNO dan cabang menjadi sangat dekat. Cabang ibarat anak yang boleh mengeluhkan semua persoalan di lapangan dan HBNO berperan sebagai orang tua yang bijak memberikan jawaban dan jalan keluar.
NU di wilayah Tasikmalaya, sebagaimana diwartakan Al-Mawaizh, berhasil membawa pencerahan pemikiran Islam, mendobrak kemapanan para ulama kaum yang dekat dengan penguasa Hindia Belanda. Padahal, ini yang masih membebani pikiran saya, para ulama kaum itu mempraktikkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Secara harafiah, mereka adzan Jumat dua kali, memulai dan megakhiri puasa dengan rukyat, tahlilan, dan lain-lain. Mereka menamakan dirinya jamaah Aswaja. Sementara NU yang digerakkan antara lain oleh Ajengan Syabandi Cilenga dan Ajengan Ruhiat Cipasung, “melawan” praktik-praktik itu. Bukan menyalahkan amaliahnya, tetapi menjelaskan bahwa amaliah Islam tidak hanya sebatas itu. NU Tasikmalaya saat itu, menggunakan hisab, adzan Jumat cukup sekali, dan tidak mewajibkan tahlil.
Kelompok Aswaja yang bermuara kepada ulama kharismatik KH Sjudja’i (Mama Kudang), terhimpun dalam Izharu Baiatil Muluk wal Umara yang didirikan pada 1920. Ini semacam embrio dari Majelis Ulama. NU muncul sebagai “perlawanan” atas kelompok ini, sekalipun notabene tokoh-tokohnya seperti Ajengan Ruhiat masih terhitung santri dari Mama Kudang. Maka populerlah dua kelompok: Izhar dan Nahdloh.
Perdebatan dengan kelompok Aswaja ini berlangsung lama dan “keras” yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Dari sini bisa dipahami kenapa di Jawa Barat tidak semua pengamal aswaja ikut NU.
Di penghujung 1930-an, keduanya mulai kehilangan alasan untuk berdebat, ketika Muhammadiyah mulai menggeliat dan Persis melalui A. Hasan mulai berpropagada menyerang amaliah ormas Islam yang lain. Izhar dan Nahdloh menjadi tersudut dan secara alamiah keduanya bersama-sama menjawab setiap tantangan debat dengan A. Hasan.
Perjalanan bangsa ini kemudian, revolusi dan pemberonakan DI/TII, ikut membaurkan kelompok Izhar dengan Nahdloh. Tak terhitung keturunan dari kelompok Izhar yang menjadi pengurus NU, sekalipun yang tetap tidak mau disebut NU pun masih ada.
Dengan mengungkapkan ingatan di atas, saya tidak ingin membandingkan kondisi tahun 1930-an itu dengan sekarang, karena tiap zaman selalu berbeda cara memandang dinamika sekitarnya. Saya tertarik, pertama, dengan metode organisasi saat itu yang berhasil membedakan antara anggota dan jamaah NU. Jamaah tidak perlu tahu tetek-bengek ihwal keorganisasian NU, sementara anggota memang harus memahaminya, mau aktif dalam berbagai kegiatan, dan bersedia membayar iuran bulanan. Maka tidak semua jamaah harus menjadi anggota NU.
Saya pikir hal ini masih bisa diterapkan. Dengan cara ini PBNU bisa fokus memberdayakan anggota dan mendorong mereka untuk “menggarap” jamaah masing-masing. PBNU tidak lagi terbebani oleh jumlah jamaah yang puluhan juta itu, cukup menggarap anggota yang terdaftar, terseleksi, dan “setia”.
Kedua, dalam public-campaign ke dalam maupun keluar NU, secara prinsip tidak lagi membatasi NU pada amaliah tertentu, bahwa seolah-olah NU hanya ditandai oleh adanya amaliah tersebut, bahwa tanpa amaliyah itu NU akan hilang. Pada kenyataannya banyak ulama NU yang tidak menjalankan amaliyah tertentu itu dan mereka tetap dihormati.
Pengakuan NU pada empat mazhab harus benar-benar diamalkan agar jamiyyah NU bisa menjadi rumah besar bersama bagi praktik amaliyah empat mazhab itu. PBNU bisa memosisikan diri sebagai sentrum bagi praktik empat mazhab di Indonesia.
Kalau dua hal itu bisa dijadikan fundamen pembenahan internal, kita bisa mulai mencari cara efektif menghadapi “serangan” kompetitor dari eksternal. Misalnya soal cara menghadapi kelompok-kelompok yang menyerang amaliyah yang diakui NU, jangan lagi dihadapi dengan model perdebatan. Koridor hukum Indonesia memberi peluang bagi warganya untuk melaporkan hal-hal yang meresahkan masyarakat kepada aparat hukum. Kalau “serangan” itu berupa ceramah pengajian, secara terbuka melalui media cetak atau elektronik, itu bisa direkam atau difoto kopi, untuk di lampiran sebagai bukti pelaporan. Pengurus NU sampai pada tingkat ranting harus diberikan pelatihan hukum, bagaimana cara membuat laporan yang benar kepada kepolisian dan aparat hukum yang lain terhadap potensi yang mengancam kerukunan sosial di lingkungannya.
Kita harus mulai memberikan pelajaran kepada para kompetitor, bahwa tatanan sosial yang sudah disepakati warga secara turun-temurun, tidak boleh dirusak oleh kepentingan dakwah tertentu. Energi pengurus, anggota dan jamaah NU yang terselamatkan melalui cara ini, dengan sendirinya akan tersalurkan pada hal-hal lain yang terabaikan atau bahkan belum terpikirkan. Tidak ada lagi kekhawatiran adanya gangguan pihak lain. Memperbaiki kurikulum pendidikan, memulai lagi koperasi sebagai sendi ekonomi jamaah, memperkuat mabarrot, di antara hal-hal yang akan tergarap.
Di sisi lain, PBNU secara aktif harus menjelaskan kepada lembaga-lembaga berwenang di tingkat nasional, agar tidak lagi memberi peluang bagi munculnya kelompok-kelompok yang hanya akan merusak ikatan kebangsaan dan terus menerus membawa bangsa ini kepada konflik internal Islam yang tidak berkesudahan. Secara khusus, PBNU mendesak dan memberi pengertian kepada kepolisian dan aparat hukum lain, agar menindaklanjuti setiap laporan pengurus NU di berbagai level.
Kemudian dalam menghadapi kontestasi politik yang selama ini hanya menempatkan NU pada posisi “penumpang”, PBNU seyogianya mulai membentuk atau menunjuk sejumlah pesantren untuk membuka semacam madrasah siyasiyyah. Sekolah kader politik NU. Di sini diajarkan semua hal tentang politik, menyusun strategi, cara mendapatkan dana dan berkampanye, juga etika politik. Dilakukan secara periodik (angkatan) dan pesertanya didatangkan dari seluruh cabang NU dengan kualifikasi tertentu. Jadi, benar-benar ada pelatihan politik yang menyiapkan anak muda NU untuk berkompetisi dalam medan politik di tingkat lokal hingga nasional. Alumninya disebar ke berbagai partai, bukan eksklusif untuk satu partai saja. Sejarah sudah cukup memberi pelajaran, terpaku pada satu partai hanya mengkerdilkan NU. Mereka bisa memilih, sesuai situasi-kondisi daerahnya, partai mana yang lebih maslahat untuk kepentingan jamiyyah NU. Dengan cara ini NU benar-benar bisa jadi “orang tua” bagi “anak-anak” yang berbeda-beda partai tetapi dengan satu tujuan kemaslahatan NU.
'Ala kulli hal, semoga ini bukan sekadar mimpi. Wallahu a’lam.
Penulis adalah Direktur Media Center PWNU Jawa Barat
Terpopuler
1
Wacana WhatsApp Premium Dikritik, Dosen Unusia: Jangan Tambah Beban Rakyat
2
Wamenag: Urusan Haji Bukan Lagi Tugas Kemenag, Kini Fokus pada Layanan Keagamaan dan Pendidikan
3
DKM Nurul Hidayah Salurkan Beasiswa untuk Siswa RT 11 dan 12 Bojonggede
4
Saat Uang Haram Dianggap Rezeki dan Digunakan untuk Ibadah
5
LTNNU Depok Apresiasi PWI atas Dukungan Pemberitaan Kegiatan Keumatan
6
Kesempurnaan Ajaran Agama
Terkini
Lihat Semua